
tes skolastik 4
Authored by sopyan hadi
Physical Ed
2nd Grade - Professional Development
Used 3+ times
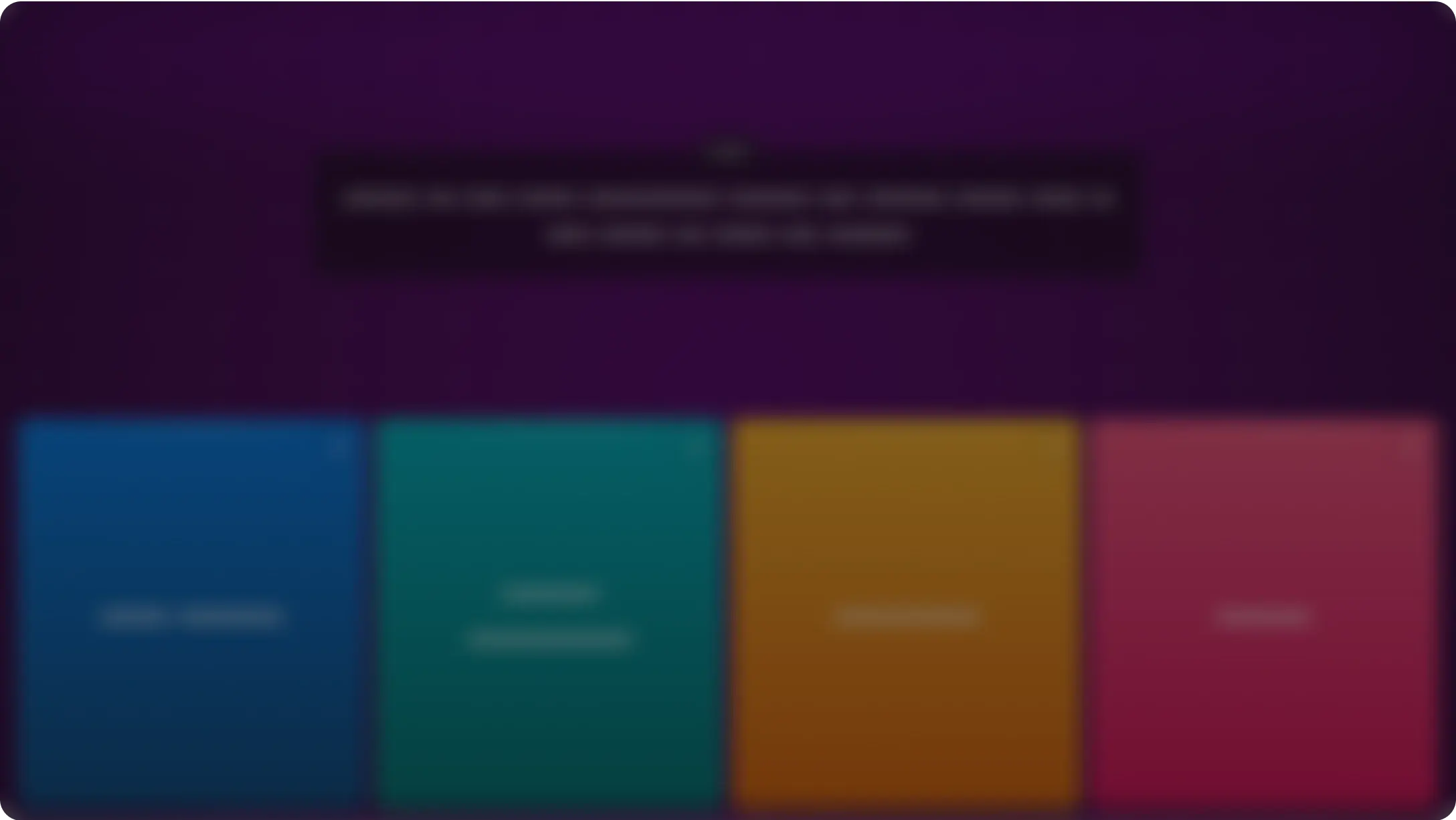
AI Actions
Add similar questions
Adjust reading levels
Convert to real-world scenario
Translate activity
More...
Content View
Student View
31 questions
Show all answers
1.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
2 mins • 1 pt

Kawasan Halimun boleh dibilang merupakan kawasan yang tidak jelas orientasi pengelolaannya, ibarat mata uang yang memiliki dua sisi. Di satu sisi merupakan kawasan yang dikelola untuk tujuan konservasi, di sisi lain menjadi kawasan eksploitasi. Tabel berikut ini secara umum menunjukkan tumpang tindih kawasan Halimun dengan berbagai kepentingan dan melahirkan konflik lahan yang tak berkesudahan
Di sisi lain dalam proses pembangunan selama ini, pihak masyarakat yang secara turun-temurun mendiami dan menggantungkan hidupnya dari kawasan ini hanya menjadi objek. Posisi masyarakat semakin terpinggirkan (termarginalisasi), bahkan pelabelan yang bersifat negatif disematkan untuk masyarakat yang tinggal di kawasan ekosistem Halimun dengan tidak adil. Mereka sering disebut dengan kata perambah hutan, peladang liar, atau penebang kayu ilegal. Sebutan ini dituduhkan pada masyarakat yang hidup dan tinggal di kawasan konservasi. Bahkan, pemerintah sendiri cenderung memberikan nama untuk suatu kegiatan masyarakat tersebut. Contohnya adanya kegiatan pemberian bantuan kambing dari pemerintah untuk masyarakat sekitar hutan sebagai salah satu program yang ditunjukkan untuk mengurangi perambahan hutan di kawasan Halimun oleh masyarakat.
Persoalan yang juga mengemuka di kawasan Halimun ialah akses dan hak masyarakat dalam mengelola sumber daya alam di kawasan ini yang semakin dibatasi dan dihilangkan. Hasil pemetaan partisipatif yang dilakukan oleh masyarakat di tiga desa di kawasan Halimun dengan difasilitasi RM dan Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP) nenunjukkan bahwa lahan yang bisa diakses dan dikelola oleh masyarakat hanya sekitar 4,20%-18,58% dari luas areal yang dialokasikan secara administrasi oleh pemerintah.
Akar permasalahan yang berkecamuk di kawasan ekosistem Halimun disebabkan oleh persepsi atau pandangan dan pemahaman yang berbeda tentang kawasan Halimun di antara masyarakat serta pihak-pihak lain, yaitu negara/ pemerintah dan perusahaan yang kemudian dimanifestasikan dalam kebijakan yang juga masih tumpang-tindih dan bersifat sektoral sehingga memunculkan berbagai konflik salah satunya konflik lahan. Sebagai contoh, kawasan Halimun ditetapkan menjadi Taman Nasional Gunung Halimun sejak tahun 1992 dengan luas 40.000 ha dan diperluas menjadi 113.375 ha pada tahun 2003. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa dalam kawasan yang telah ditetapkan menjadi kawasan konservasi, ternyata masih dialokasikan juga untuk areal eksploitasi tambang emas, perak, dan bentonit; areal perkebunan teh PT Ciangsana; dan hutan produksi yang dikelola PERHUTANI dengan tanaman pinus.
Diadaptasi dari: Menepis Kabut Halimun (Hendarti)
Berdasarkan paragraf pertama, mengapa kawasan Halimun dapat diibaratkan sebagai mata uang yang memiliki dua sisi?
A. Kawasan Halimun merupakan kawasan yang dikelola untuk tujuan konservasi.
B. Kawasan Halimun memiliki berbagai sumber daya alam yang dapat menghasilkan uang.
C. Kawasan Halimun merupakan kawasan yang tidak jelas orientasi pengelolaannya.
D. Kawasan Halimun menjadi kawasan eksploitasi
E. Kawasan Halimun penghasil emas, perak, dan bentonit.
2.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
2 mins • 1 pt

Kawasan Halimun boleh dibilang merupakan kawasan yang tidak jelas orientasi pengelolaannya, ibarat mata uang yang memiliki dua sisi. Di satu sisi merupakan kawasan yang dikelola untuk tujuan konservasi, di sisi lain menjadi kawasan eksploitasi. Tabel berikut ini secara umum menunjukkan tumpang tindih kawasan Halimun dengan berbagai kepentingan dan melahirkan konflik lahan yang tak berkesudahan
Di sisi lain dalam proses pembangunan selama ini, pihak masyarakat yang secara turun-temurun mendiami dan menggantungkan hidupnya dari kawasan ini hanya menjadi objek. Posisi masyarakat semakin terpinggirkan (termarginalisasi), bahkan pelabelan yang bersifat negatif disematkan untuk masyarakat yang tinggal di kawasan ekosistem Halimun dengan tidak adil. Mereka sering disebut dengan kata perambah hutan, peladang liar, atau penebang kayu ilegal. Sebutan ini dituduhkan pada masyarakat yang hidup dan tinggal di kawasan konservasi. Bahkan, pemerintah sendiri cenderung memberikan nama untuk suatu kegiatan masyarakat tersebut. Contohnya adanya kegiatan pemberian bantuan kambing dari pemerintah untuk masyarakat sekitar hutan sebagai salah satu program yang ditunjukkan untuk mengurangi perambahan hutan di kawasan Halimun oleh masyarakat.
Persoalan yang juga mengemuka di kawasan Halimun ialah akses dan hak masyarakat dalam mengelola sumber daya alam di kawasan ini yang semakin dibatasi dan dihilangkan. Hasil pemetaan partisipatif yang dilakukan oleh masyarakat di tiga desa di kawasan Halimun dengan difasilitasi RM dan Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP) nenunjukkan bahwa lahan yang bisa diakses dan dikelola oleh masyarakat hanya sekitar 4,20%-18,58% dari luas areal yang dialokasikan secara administrasi oleh pemerintah.
Akar permasalahan yang berkecamuk di kawasan ekosistem Halimun disebabkan oleh persepsi atau pandangan dan pemahaman yang berbeda tentang kawasan Halimun di antara masyarakat serta pihak-pihak lain, yaitu negara/ pemerintah dan perusahaan yang kemudian dimanifestasikan dalam kebijakan yang juga masih tumpang-tindih dan bersifat sektoral sehingga memunculkan berbagai konflik salah satunya konflik lahan. Sebagai contoh, kawasan Halimun ditetapkan menjadi Taman Nasional Gunung Halimun sejak tahun 1992 dengan luas 40.000 ha dan diperluas menjadi 113.375 ha pada tahun 2003. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa dalam kawasan yang telah ditetapkan menjadi kawasan konservasi, ternyata masih dialokasikan juga untuk areal eksploitasi tambang emas, perak, dan bentonit; areal perkebunan teh PT Ciangsana; dan hutan produksi yang dikelola PERHUTANI dengan tanaman pinus.
Diadaptasi dari: Menepis Kabut Halimun (Hendarti)
Berdasarkan tabel data ekstraksi di kawasan Halimun oleh berbagai pihak, manakah pernyataan berikut yang paling tidak benar?
A. PT Aneka Tambang (Gunung Pongkor, Bogor, Jawa Barat) telah beroperasi sejak tahun 1992 sampai sekarang dan produk yang dihasilkan adalah getah karet (latex).
B. PT UNOCAL merupakan salah satu PT yang tidak diketahui sejak kapan berdirinya dan produk yang dihasilkan adalah gas alam.
C. PERHUTANIl (BKPH) sudah beroperasi sejak tahun 1978 sampai sekarang dan produk yang dihasilkan, yaitu pinus kayu, mahogany kayu, meranti getah, dan pinus.
D. PT Ciangsana adalah PT yang durasi pengoperasiannya hanya 20 tahun dan menghasilkan teh, sedangkan luas areal dan produksi per tahunnya tidak diketahui.
E. PT Sari Gunung Indah (SGI) telah beroperasi sejak tahun 1983 sampai sekarang dan menghasilkan emas dan perak, sedangkan produksi pertahunnya sebanyak 13.069.032,00 kg.
3.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
2 mins • 1 pt
Berdasarkan tabel data ekstraksi di kawasan Halimun oleh beberapa pihak. Berapakah perbandingan jumlah produksi teh hijau dan teh hitam yang dihasilkan dari PT Nirmala dan PTPN VIl per tahunnya?
A. 1:20
B. 2:60
C. 3:15
D. 5:15
E. 15:30
4.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
2 mins • 1 pt
Berdasarkan paragraf kedua, hal apakah yang mungkin dapat terjadi jika masyarakat di kawasan tersebut tidak hanya dijadikan objek oleh pemerintah?
A. Tingkat perekonomian masyarakat semakin membaik.
B. Masyarakat dapat mengelola sumber daya alam dengan bebas.
C. Masyarakat tidak dapat menebangi pohon secara ilegal.
D. Masyarakat akan mendapat banyak bantuan kambing dari pemerintah agar memiliki kesibukan lain.
E. Masyarakat mendapat pelabelan positif dan posisi masyarakat tidak semakin terpinggirkan.
5.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
2 mins • 1 pt
Semua orang pasti mengenal pendidikan. Pendidikan adalah proses internalisasi budaya ke dalam diri seseorang dan masyarakat sehingga membuat individu dan masyarakat menjadi beradab. Pendidikan bukan hanya sarana transfer ilmu pengetahuan, tetapi lebih luas lagi, yakni sebagai sarana pembudayaan dan penyaluran nilai, yaitu enkulturisasi dan sosialisasi. Anak harus mendapatkan pendidikan itu mencakup sekurang-kurangnya tiga hal penting mendasar.
Gagasan utama paragraf di atas...
Pendidikan dikenal setiap orang
Pendidikan adalah internalisasi budaya
Pendidikan adalah internalisasi budaya
Pendidikan merupakan sarana pembudayaan
Pendidikan harus berdimensi kemanusiaan
6.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
2 mins • 1 pt
Motivasi nonfinansial adalah dorongan yang tidak diwujudkan dalam bentuk finansial atau uang. Melainkan diwujudkan dalam bentuk pujian, penghargaan. pendekatan antar manusia dan lain sebagainya. Dari penjelasan ini, dapat disimpulkan bahwa motivasi sangat penting bagi suatu perusahaan atau instansi karena dapat mendorong karyawan untuk bekerja totalitas dalam mencapai tujuan perusahaan secara efisien.
Kata ini pada kalimat ketiga merujuk pada ….
motivasi finansiial dan nonfinansiial
dampak motivasi
imbalan finansial
pemberian motif
konsep dan jenis motivasi
7.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
2 mins • 1 pt
Domestikasi hewan diduga telah dilakukan manusia pada saat belum mengenal budidaya dan merupakan kegiatan pemeliharaan serta pembudidayaan hewan yang pertama kali.
Makna istilah domestikasi dalam kalimat di atas adalah ...
Proses mengadopsi hewan liar ke dalam kehidupan manusia
Proses menjinakkan hewan liar untuk kepentingan hidup manusia
Proses menyeleksi dan memperbaiki keturunan hewan liar
Proses perubahan perilaku dari organism hewan liar
Proses memelihara dan membudidayakan hewan
Access all questions and much more by creating a free account
Create resources
Host any resource
Get auto-graded reports

Continue with Google
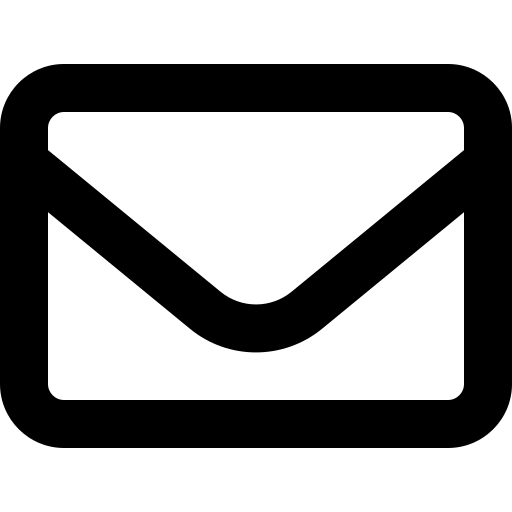
Continue with Email

Continue with Classlink

Continue with Clever
or continue with

Microsoft
%20(1).png)
Apple
Others
Already have an account?
Similar Resources on Wayground

29 questions
ORIENTACION
Quiz
•
5th - 8th Grade

30 questions
SENAM LANTAI
Quiz
•
10th - 12th Grade

29 questions
sains upsr
Quiz
•
5th - 6th Grade

35 questions
Latihan PTS Kelas 6
Quiz
•
6th Grade

30 questions
PTS GENAP TAHUAN AJARAN 2023-2024
Quiz
•
10th Grade

26 questions
Sport e Sani Stili di Vita
Quiz
•
6th - 8th Grade

28 questions
1. PJOK KELAS X
Quiz
•
10th Grade

30 questions
PTS PJOK KLS 8
Quiz
•
12th Grade
Popular Resources on Wayground

7 questions
History of Valentine's Day
Interactive video
•
4th Grade

15 questions
Fractions on a Number Line
Quiz
•
3rd Grade

20 questions
Equivalent Fractions
Quiz
•
3rd Grade

25 questions
Multiplication Facts
Quiz
•
5th Grade

22 questions
fractions
Quiz
•
3rd Grade

15 questions
Valentine's Day Trivia
Quiz
•
3rd Grade

20 questions
Main Idea and Details
Quiz
•
5th Grade

20 questions
Context Clues
Quiz
•
6th Grade
Discover more resources for Physical Ed

5 questions
History of the Winter Olympics
Interactive video
•
1st - 6th Grade

10 questions
American Football Rules
Quiz
•
7th Grade

20 questions
Muscular System
Quiz
•
7th Grade

19 questions
Winter Olympics - Part 1
Quiz
•
8th Grade

10 questions
First Aid, CPR, Emergency Response Unit
Quiz
•
7th Grade

40 questions
Mental and Emotional Health Review
Quiz
•
6th Grade

28 questions
Exercising Safely - Fitness Components
Quiz
•
12th Grade

10 questions
Understanding Body Composition and Fitness
Interactive video
•
5th - 8th Grade