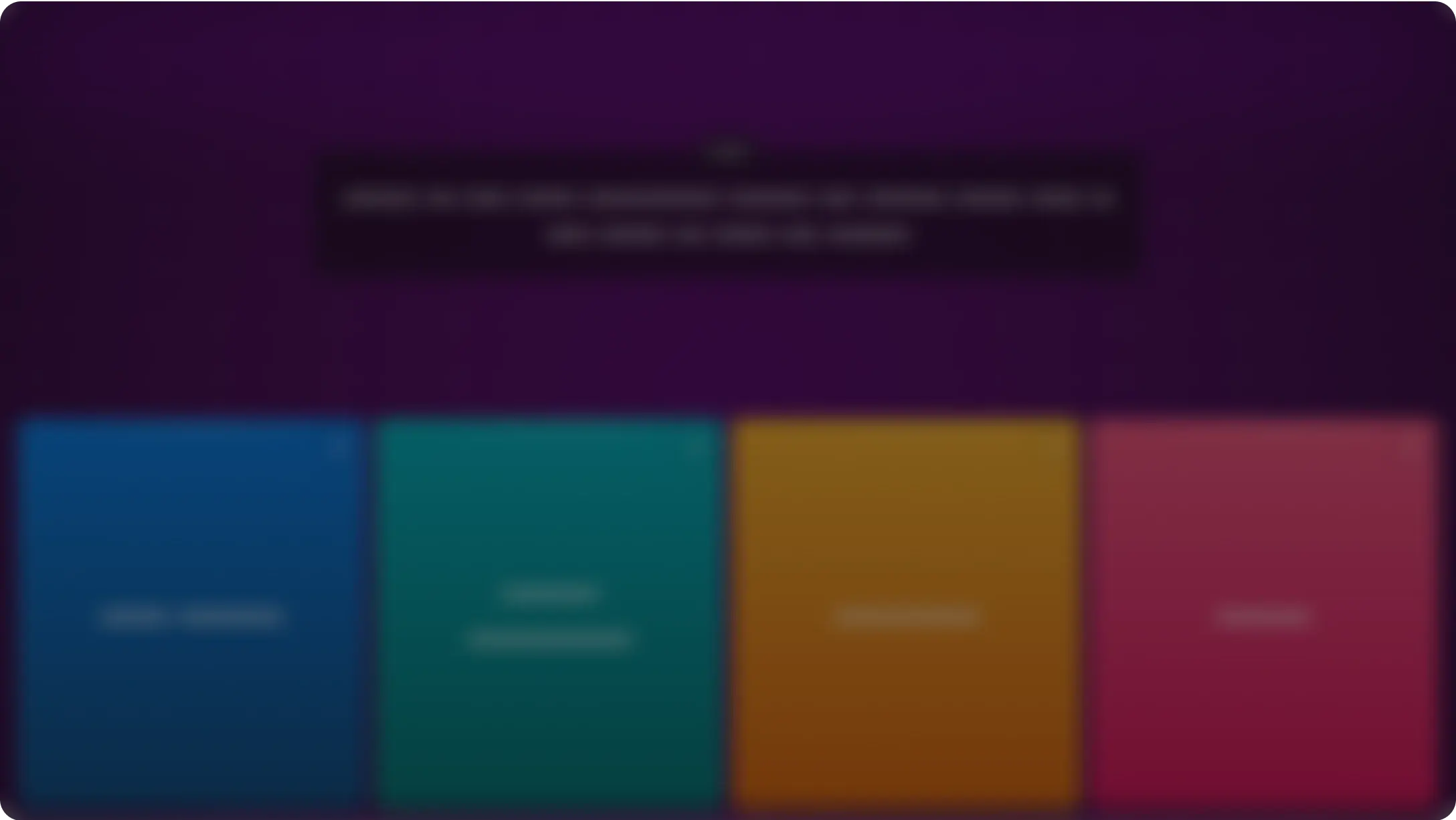Penyandang disabilitas masih kerap menjadi korban ableisme. Ableisme adalah stereotipe dan prasangka terhadap penyandang disabilitas sebagai orang yang dianggap inferior dan tak berdaya. Bahkan, terkadang disertai semangat untuk “memperbaiki” mereka agar menjadi “normal” dan mampu melakukan berbagai hal.
Bentuk konkret praktik ableisme dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Di media, misalnya, pemberitaan tentang penyandang disabilitas lebih sering memunculkan mereka sebagai orang yang menderita atau perlu dikasihani. Praktiknya juga telah mengakar dalam sistem kenegaraan. Sistem pendidikan di Indonesia, misalnya, selama ini memisahkan siswa penyandang disabilitas. Mereka harus menempuh sekolah khusus agar tidak bercampur dengan siswa yang dianggap “normal”. Seakan ada dikotomi bahwa sekolah umum adalah untuk siswa yang dikatakan “normal”, sementara siswa yang memiliki disabilitas disediakan sekolah luar biasa (SLB).
Meluasnya perspektif ableisme terjadi disebabkan oleh paradigma dalam melihat persoalan disabilitas. Masyarakat kebanyakan masih memandang disabilitas melalui paradigma sosial, yakni melihat isu disabilitas sebagai sebuah permasalahan sosial. Paradigma ini memosisikan penyandang disabilitas sebagai kelompok yang butuh belas kasihan dan sebagai objek yang tidak berdaya sehingga perlu dibantu oleh lingkungan sekitar dan juga negara.
Untuk mengubah stigma ini, persoalan disabilitas perlu dilihat menggunakan paradigma HAM. Paradigma ini melihat bahwa penyandang disabilitas setara dengan warga negara yang lain, hanya saja memiliki kebutuhan yang berbeda sehingga negara perlu memperhatikan dan memenuhi kebutuhan tersebut. Paradigma HAM ini menekankan pada menghilangkan hambatan fisik dan sosial sehingga penyandang disabilitas memiliki kemandirian, pilihan, serta kontrol. Dalam paradigma ini, pengambilan dan perubahan kebijakan mensyaratkan keterlibatan penuh penyandang disabilitas.
Sumber: theconversation.com/id (dengan modifikasi)